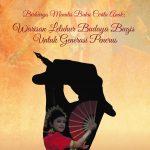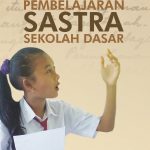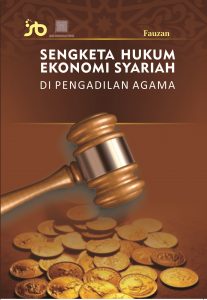
Samudrabiru – Di Indonesia, penyelenggaraan peradilan diatur dlam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negra hukum republic Indonesia.
Dalam kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah salah satu pranata (institusi) dalam memenuhi hajat hidup anggota masyarakat untuk menciptaskan dan menegakkan hukum serta keadilan. Sementara pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan.
Dari ungkapan di atas bahwa lembaga peradilan memegang peranan yang sangat penting di dalam menggiring terciptanya sebuah Negara hukum. Hukum harus menjadi titik sentral pijakan dalam berprilaku baik secara individual, masyarakat, maupun dalam berbangsa maupun bernegara. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga peradilan beserta perangkat hukumnya terutama hakim yang harus betul-betul mampu untuk berprilaku baik dan sungguh-sungguh untuk menjaga kehormatan sebagai seorang penegak hukum dalam sebuah peradilan. Sebagaimana jimly ,mengatakan, bahwa inti dari Negara hukum adalah hakim itu sendiri.
Peradian agama sebgaai salah satu lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat di Indonesia. Hal ini tercermin dari tiga pilar yang dimiliki oleh peradilan agama sebagai syarat berlakunya sebuah peradilan pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan undang-undang, Kedua, adanya organ pelaksana, dan Ketiga adanya sarana hukum sebagai rujukan.
Pada pilar pertama terlihat bahwa secra legalistic hal ini terungkap pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana peradilan agama diakui secara resmi sebagi salah satu pelaksana judicial power dalam Negara hukum republic Indonesia. Begitu juga pada pilar kedua, secara historis peradilan agama sebenarnya telah punya organ atau pejabat pelaksanaan dalam menjalankan peradilan. Walaupun di dalam perkembangannya m,asih terdapat kekurangan terutama profesionalisme dari organ aparat yang beum memenuhi standar. Namun, sering dengan pembinaan dan pengawasan oleh departemen agama dan mahkamah Agung maka lambat laun peradilan agama dan aparatnya diharapkan bias mencapai tingkat integritas profesionalisme yang berkualiatas. Pada pilar terahir tentang adanya sarana hukum sebagai rujukan, maka hal ini tidak terlepas dari kehadiran sarana hukum positif yang pasti dan secara unifikasi serta didukung dengan kedudukan dan kewenangan peradilan agama yang telah terkodifikasi aturan hukumnya, termasuk hukum acaranya. Dari sinilah bias terlihat bahwa adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (sebelum di ubah) telah menunjukan adanya kedudukan dan kewenangannya yang mantap.
Begitu juga dengan hukum acara yang telah berlaku pada peradilan agama disamakan dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Dalam hal ini, sumber hukum material pengadilan agama m,engacu kepada alquran, sumber yang paling tinggi setelah al-quran adalah sunnah atau hadis nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam tertinggi yang berupa akal adalah ijma, yang merupakan ketetapan dari para ulama besar Islam. Sumber hukum Islam dibawah Ijma adalah Qiyas. Qiyas dipakai dalam keadaan bahwa tidak ada ketentuan hukum Islam tertentu untuk suatu perkara antara umat Islam. Istibsan juga termasuk dalam sumber hukum islam setelah qiyas. Istibsan hanya dipakai untuk alas an yang kuat seperti ketidakadilan, kepentingan masyarakat atau keadaan darurat. Urf yang merupakan kebiasaan atau adat juga termasuk di dalam sumber hukum islam . Urf bersifat dinamis karena diubah sesuai dengan perkembangan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian hukum Islam menempati kedudukan yang penting dalam system hukum Indonesia. Sehingga di dalam sejarah Indonesia ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.
Pasca reformasi, berdasarkan TAP MPR RI. No.X/ MPR/ 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25, maka kemudian lahirlah Undang-Undang baru yaitu Nomor 35 Tahun 1999 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kembali menegaskan perubahan sistem pengelolaan lembaga peradilan yang tadinya menggunakan sistem dua atap menjadi satu atap, dan proses pengalihan pengelolaan lembaga peradilan dibawah mahkamah agung harus selesai selama lima tahun.
Konsep satu atap pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Proses pengalihan penyatuatapan tersebut juga berimplikasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian realisasi pengalihan tersebut diterbitkan keputusan presiden No. 21 Tahun 2004, tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilingkungan peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama.
Dari sisi kewenangannya, peradilan agama bersifat khusus, karena kewenangan peradilan agama selama ini memerlukan pendekatan yang berbeda dari permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Selama ini peradilan agama hanya mengadili dan meyelesaikan sengketa hanya terbatas kepada persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan shadaqah. Itupun tidak semua bidang menjadi wewenang penuh peradilan agama, karena pada prakteknya ada sebagian bidang yang bisa diberikan pilihan hukum bagi para pencari keadilan. Di antara bidang-bidang yang bisa diberikan pilihan kepada pencari keadilan adalah bidang kewarisan. Hal ini terungkap pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa persoalan waris merupakan persoalan opsional, artinya bagi para pencari keadilan harus menentukan hukum apa yang ingin di capai, (hukum adat atau hukum Islam) dan lembaga peradilan mana yang dikehendaki (agama atau umum).
Namun saat ini, persoalan-persoalan syariah tidak terbatas hanya pada kedelapan bidang yang telah disebutkan dalam undang-undang, tapi menyangkut seluruh kehidupan dalam masyarakat, termasuk didalamnya persoalan ekonomi Islam yang tumbuh dengan pesatnya pada tahun 90-an. Hal itu ditandai dengan menguatnya sistem perbankan syariah dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 serta keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 , yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejak itu, perbankan syariah terus bermunculan.
Dalam perkembangannya, ekonomi syariah tidak terbatas pada perbankan syariah saja, tetapi diikuti dengan bermacam-macam bisnis-bisnis yang lain yang menggunakan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, rekayasa dana syariah, dan lain sebagainya. Pada dasarnya hubungan-hubungan tersebut merupakan perjanjian Islam yang dikenal dengan muamalah. Disatu sisi bagi umat Islam kenyataan tersebut merupakan hal yang mengembirakan, namun disisi lain timbul persoalan ketika antara pelaku bisnis ekonomi syariah tersebut terjadi perselisihan. Memang pada awalnya dilakukan upaya penyelesaian dengan musyawarah menggunakan hukum Islam, tetapi tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.
Sebelumnya, penyelesaian sengketa hukum ekonomi Islam dilakukan dengan mekanisme peradilan. Dalam hal ini peradilan umum, termasuk menggunakan media BAM (Badan Arbitrase Muamalah), yang kemudian diganti dengan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Namun, sebagai lembaga arbitrase dilihat dari kekuatan hukumnya pada aturan perundang-undangan tidak memiliki legalitas formal yang kuat, sehingga hasil putusan dari Basyarnas tersebut bisa diingkari oleh pihak yang bersengketa, sebab putusan yang diambil oleh basyarnas hanya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karenanya, jika sengketa itu tidak bisa diselesaikan oleh basyarnas, maka pihak yang bersengketa bisa membawanya kepada peradilan umum.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian di revisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama merupakan solusi dari persoalan yang mengemuka pada periode sebelumnya khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Akan tetapi perluasan kewenangan bagi peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 butir h dalam menangani perkara ekonomi Islam sebenarnya bukan tanpa masalah. Perluasan kewenangan ini berdampak kepada adanya ketersinggungan antara kewenangan peradilan umum dan peradilan agama yang sama-sama berwenang menyelesaikan perkara perdata dalam ekonomi syariah. Terlebih ketika melihat penjelasan Pasal 49 mengenai orang-orang tertentu, yaitu antara “orang-orang yang beragama Islam”. Dalam penjelasan Pasal 49 tersebut dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk “orang” atau “badan hukum”. Dari kata “badan hukum” ini memunculkan masalah ketika disejajarkan dengan “orang yang beragama Islam”. Kata ini akhirnya menjadi kata yang problematik, bagaimana akan mengukur ”badan hukum” beragama Islam?
Padahal, penjelasan Pasal 49 UU peradilan agama menyatakan, “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk “orang” atau “badan hukum” yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Persoalaanya adalah standar apa yang dipakai dalam katagori pendundukan secara sukarela tersebut?
Meskipun demikian, permasalahan hukum diatas perlu direspon positif sebagai upaya pembangunan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia dan juga sebagai bentuk dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang progresif dan demokratis. Peradilan agama sebagai sebuah peradilan yang mengalami perjalanan panjang sampai saat ini menurut penulis mutlak adanya, sehingga permasalahan-pemasalahan dalam hal perluasan kewenangan mengenai sengketa ekonomi syariah oleh peradilan agama perlu untuk dicari langkah-langkah solusi. Termasuk hal kekhawatiran terhadap kapasitas pemahaman hakim pengadilan agama dalam urusan ekonomi syari’ah, karena tanpa didukung pengetahuan yang memadai justru akan menciptakan persoalan baru, yaitu kepastian dan keadilan hukum, sehingga menjadi bumerang bagi peradilan agama secara umum.
Judul : Sengketa Hukum Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama
Penulis : Fauzan
Penerbit : Samudra Biru, Cetakan I, Oktober 2018
Dimensi : viii + 140 hlm. ; 14 x 20 cm.
Harga : Rp