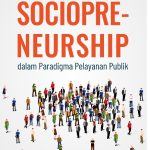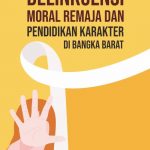Samudrabiru- Mendengar ada seorang anak cacat yang parah pada keluarga di suku Iban (orang pribumi Sarawak, Malaysia), dua orang pekerja sosial berinisiatif mendatanginya. Mereka bermaksud memberikan bantuan karena di tempat ini amat jarang masyarakat mendatangi pekerja sosial untuk meminta bantuan.
Tak dinyana, begitu memasuki area kampung mereka diusir oleh orang tua anak dengan parang terhunus. Mereka akhirnya menyadari sikap orang tua itu disebabkan adanya kepercayaan tentang karma – sebuah keyakinan dalam ajaran Budha.
Dalam kepercayaan karma, seorang anak yang mengalami kecacatan adalah hukuman bagi orang tua karena diyakini telah melakukan kesalahan di masa lalu. Maka anak harus dilindungi, tidak boleh dibawa pergi orang lain dan melarang orang luar mana pun untuk melihat sang anak (hlm. 87).
Analogi sederhana yang sering disematkan pada pekerja sosial dengan sebuah kisah tentang seseorang yang sedang menyelamatkan seekor anjing liar yang terlilit sebuah tali pada sebatang pohon, lalu setelah anjing tersebut lepas lantas menggigit si penolong tersebut, ternyata benar adanya.
Aktivitas memberi bantuan di negara-negara Timur seperti halnya Indonesia ataupun Malaysia tampaknya harus menciptakan bentuk tersendiri. Tidak bisa mengimpor begitu saja budaya praktek pekerjaan sosial dari Barat di mana ilmu ini muncul dan berkembang.
Oleh karena itu, pribumisasi pekerjaan sosial – sebagaimana yang menjadi ide kunci buku ini – adalah sebuah keniscayaan. Seorang akademisi ataupun praktisi pekerjaan sosial akan mengalami ‘gagap budaya’ jika tidak melakukan upaya pribumisasi. Penulis buku ini pun mengisahkan sempat mengalami ‘gagap budaya’ tersebut.
Ketika menempuh pendidikan di Australia pada 1979-1980, Ling How Kee tentu mendapatkan segudang teori ataupun metode tentang praktik pekerjaan sosial. Namun begitu berpraktek kembali di Sarawak, Malaysia, How Kee seperti mengalami benturan kebudayaan.
Misalnya ketika berhadapan dengan masalah kecacatan, How Kee mendapati bahwa orang Melayu ternyata tidak sedikit pun memiliki rasa malu ataupun rasa bersalah. Bagi orang Melayu, anak adalah karunia yang maha agung dari Allah Swt. Kondisi ini sangat berbeda dengan budaya Barat atau orang China sebagaimana latar belakang sang penulis.
Misalnya budaya China mengenal feng shui, sehingga jika ada anak terlahir cacat maka ini berkaitan dengan feng shui yang salah, atau hukuman atas dosa masa lalu, dan oleh karena itu, malu dan bersalah tidak terhindarkan (hlm. 3).
Adanya perbedaan budaya akan menuntut adanya perbedaan nilai, teori ataupun metode.
Terlebih lagi, nilai, teori ataupun metode pekerjaan sosial yang dipelajari oleh para akademisi di perguruan tinggi selama ini dihasilkan oleh budaya yang nota bene berasal dari Barat. Buku ini sungguh telah menyadarkan kepada para pembaca tentang adanya perbedaan ini dan pentingnya untuk melakukan upaya-upaya akademik khususnya pribumisasi (indigenisasi).
Perbedaan budaya ini makin terasa signifikan ketika kita menyaksikan tak berfungsinya lagi nilai yang selama ini dianggap sakral dalam pekerjaan sosial, misalnya nilai self determination (kebebasan diri untuk berkehendak). Seperti dimafhumi, nilai ini dikembangkan oleh budaya liberal Barat yang menjunjung tinggi kebebasan. Nilai ini menjadi mentah ketika berhadapan dengan masyarakat Timur yang cenderung pasif ketika mengalami masalah.
Seseorang misalnya, ketika mengalami masalah maka pihak keluarga besar turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pekerja sosial bahkan dituntut untuk memberikan solusi atau nasehat dan tidak hanya sekedar memberikan alternatif-alternatif saja.
Jika budaya pekerjaan sosial dan budaya masyarakat digambarkan dengan dua lingkaran yang saling berhimpitan, maka dua lingkaran tersebut akan membentuk sebuah irisan. Irisan ini menurut penulis buku ini bagaikan simbol hubungan dialogis antara budaya pekerjaan sosial dengan budaya lokal.
Suatu keseimbangan yang dinamis antara budaya lokal dengan budaya pekerjaan sosial yang memungkinkan munculnya suatu budaya ketiga (hlm. 175). Dengan cara ini, tidak satu budaya pun yang dilenyapkan atau dikecilkan, tetapi keduanya akan terus mengitari satu sama lain, tetapi tidak memasukan satu sama lain. Pribumisasi pekerjaan sosial pada dasarnya adalah upaya mengembangkan budaya ketiga ini.
Sebagai proses dialektika antara budaya praktek pekerjaan sosial dan budaya masyarakat, pribumisasi selanjutnya bersinggungan dengan otentisasi/pengaslian (authentisation). Jika pribumisasi (indigenization) bertumpu pada model Barat lalu disesuaikan dengan situasi lokal, maka otentisasi berangkat dari sisi internal dalam menggerakkan dan mengembangkan budaya praktek pekerjaan sosial.
Yang pertama perspektif orang luar, yang terakhir orang dalam (hlm. 28). Di sinilah posisi ‘internasional yang multibudaya’ yang berada di atas keduanya. Suatu pendekatan multibudaya yang signifikan dalam kaitannya dengan pribumisasi ini.
Meskipun buku ini tidak lain adalah hasil penelitian penulis di Sarawak, Malaysia, tapi kesimpulannya sangat relevan untuk konteks Indonesia. Apalagi, Indonesia dengan Malaysia dikenal sebagai negeri serumpun. Banyak sekali budaya ataupun adat kebiasaan yang sangat mirip di antara keduanya.
Maka tidak heran jika Anda membaca buku ini, mungkin Anda tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian unik dan menarik di dalamnya sesungguhnya terjadi di Malaysia bukan di Indonesia. Last but not least, buku ini sungguh menarik karena memberikan perspektif berbeda dalam budaya praktek pekerjaan sosial khususnya dalam konteks Indonesia. Selamat membaca!
Judul Buku : Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Penelitian dan Praktek di Sarawak
Penulis : Dr. Ling How Kee
Penerjemah : Drs. Juda Damanik, MSW.
Penerbit : Samudra Biru & BPSW
Cetakan : I Januari 2013
Dimensi : xvi + 224 hlm, 14,5 x 21 cm
Harga : Rp