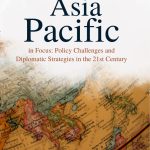Samudrabiru – Buku ini merupakan pergulatan yang panjang antara politik (yakni kekuasaan) dan Hukum Islam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cianjur Jawa Barat, bahkan mungkin saja di beberapa daerah lain yang secara terus menerus memperjuangkan penerapan syariat Islam secara legal formal.
Penerapan syariat Islam yang disuarakan oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kab. Cianjur Jawa Barat dan beberapa daerah lain, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pergulatan guna pencarian bentuk ideal hubungan antara agama dan negara.
Dalam pemikiran politik Islam, paling tidak terdapat tiga paradiqma tentang hubungan agama dan negara. Nuansa ketiga paradiqma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut.
Kendati Islam dipahami sebagai agama yang memiliki totalitas–dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik–namun sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti dunya-akhirah (dunia-kherat), din-dwlah (agama-negara).
Pasangan istilah-istilah tersebut menunjukkan adaya perbedaan koseptual dan mengesankan adanya dikotomi. Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan Negara.
Agama (Islam) dan Negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan (integrated). Wilayah agama juga meliputi wilayah politik kenegaraan. Karenanya, menurut paradiqma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan illahi” (devine sovereignity), karena kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan.
Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah. Paradigma pemikiran kelompok Syiah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dalam persoalan ini adalah imamah atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan yang memiliki fungsi keagamaan. Legitimasi kekuasaan hanya dimiliki oleh Nabi dan keturunanya.
Paradigma “penyatuan” agama dan negara juga menjadi anutan kelompok “fundamentalisme Islam” yang cenderung berorientasi kepada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Fundamentalisme Islam menekankan totalisme Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan.
Menurut salah seorang tokoh kelompok ini, al-Maududi (w.1979) syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau agama dan negara. Syariat adalah skema yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang kurang.
Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbale-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, demikian pula negara memerlukan agama.
Karena dengan negara, agama dapat berkembang, dan dengan agama, masyarakat dan rakyat dapat terarah secara moral. Pandangan semacam ini dipopulerkan antara lain oleh Mawardi (w. 1058).
Karya sangat cemerlang yang berjudul al-akhmul syulthaniyah secara jelas Mawardi menegaskan bahwa pemimpin (imamah) memiliki fungsi sebagai penerus kenabian guna memelihara agama dan dunia. (al-Mawardi: tt : hlm 5).
Seorang pemikir lain yang seide dengannya adalah Al-Ghazali (w.1111). Kendati Al-Ghazali tidak khusus sebagai pemikir politik, namun beberapa pemikiran politik yang cukup apresiatif dan signifikan dapat disimak dalam beberapa karyanya, Nashihah al-Mulk, Kimiya ash-Sa’adah, dan al-Iqtishad fi al-I’tiqad.
Dalam Nashihah al-Mulk, al-Ghazali antara lain mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam hubungan Nabi dan raja.
Menurut al-Ghazali, jika Tuhan telah mengirimkan Nabi-Nabi dan memberikan wahyu, maka Dia juga mengirim raja-raja dan memberikan “kekuatan Ilahi” (far’i izadi), keduanya memiliki tujuan yang sama : kemaslahatan kerhidupan manusia (al-maslahah zandaghani). (al-Ghazali, 1317 H, : 10).
Mungkin al-Ghazali tidak bermaksud menyamakan antara Nabi dan raja. Mungkin berarti antara agama dan negara, namun pararelisme yang dilakukannya menunjukkan status tinggi arti raja atau negara dalam hubungannya antara Nabi dan agama.
Pararelisme ini dapat ditafsirkan sebagai simbiosa yang bersifat setara. Kesimpulan ini dapat dilihat dari pendapat al-Ghzalai dalam Kimiya’ as-Sa’adah bahwa agama dan negara adalah saudara kembar (tawaaman) yang lahir dari satu ibu.(Al-Ghazali, 1940 : 59).
Konsep Far’i Izadi, yang menjadi simbiosa antara agama dan negara dalam pemikiran al-Ghazali, mempunyai akar sejarah pemikiran pra-Islam Iran. Konsep ini mengandung arti kualitas-kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara, seperti pengetahuan, keadilan dan kearifan. Kualitas-kualitas ini diyakini bersumber dari Tuhan yang bersifat “titisan” (pre-ordained).
Dengan menegaskan muatan far’i izadi dalam kepemimpinan negara al-Ghazali mungkin bermaksud menegaskan dimensi keagamaan dalam lembaga negara. Jika demikian halnya, berarti a-Ghazali sperti halnya Mawardi, juga mengenalkan suatu pendekatan realistic dalam melakukukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas penyelenggaraan negara.
Paradigma ketiga bersifat sekularistik. Paradiqma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbisostik antara agama dan negara. Sebagai gantinya paradiqma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara.
Dalam konteks Islam paradiqma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak, menolak diterminan Islam akan bentuk tertentu dari negara. Salah satu pemrakarsa paradiqma ini adalah Ali Abdur Raziq, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir.
Pada risalahnya yang diterbitkan 1925 yang berjudul Al-Islam wa Ushul al-Hukm, Ali Abdur Raziq menyebutkan bahwa Islam tidak ada kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekalifahan Khulafa ar-Rasyidin, bukanlah sebuah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem duniawi. (Diya ad-Din ar-Rais, 1973: 24).
Ali Abdur raziq sendiri menjelaskan sendiri pokok pemikirannya bahwa islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, yang diatur dalam Islam adalah bagaimana mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki, serta dengan mempertimbangkan sosial dan tuntunan zaman.(Muh. Imarah, 1972: 92).
Dalam kaitan di atas, Ali Abdul Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, tepatnya antara misi kenabian dan aktivitas politik. Dia memberikan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad seperti melakukan perang, mengumpulkan jizyah dan bahkan jihad, dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan Tuhan.
Bagi ar-Raziq, Islam adalah entitas keagamaan (wahdah diniyah) yang bertujuan mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal (jama’ah wahidah) berdasarkan keyakinan.
Dalam konteks ini Ali Abdul Raziq mengatakan: “Adalah masuk akal bagi seluruh dunia untuk mempunyai satu agama dan seluruh kemanusiaan diorganisir dalam satu kesatuan keagamaan, tetapi bahwa satu dunia dipimpin oleh satu pemerintahan adalah melampaui watak kemanusiaan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Hal semacam itu, adalah merupakan tujuan duniawi yang telah diserahkan Tuhan kepada akal kita. Dia telah memberi manusia kebebasan untuk mengatur urusan-urusan (duniawi)-nya sesuai dengan kecenderungan akal pikiran manusia. Ketentuan Tuhan adalah bahwa umat manusia harus tetap dalam kebhinekaan. (Muh Imarah, 1972: 92).
Pernyataan di atas sengaja dikutip secara lengkap karena memuat dua pengertian penting dan mendasar. Pertama istilah jama’ah yang mempunyai arti komunitas agama yang tidak mengandung komunitas politik. Kedua, meskipun itu komunitas keagamaan non-politik tetapi ia jelas membutuhkan instrument politik untuk mencapai tujuannya.
Dari pemikiran Ali Abdur Raziq dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Islam bukanlah masyarakat politik. Akan tetapi selalu ada peluang bagi masyarakat ini untuk mewujudkan bentuk pemerintahan Islam yang sesuai dengan konteks budaya.
Ali Abdul Raziq sejatinya tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam tidak menganjurkan pembentukan sebuah negara, sebaliknya justru menurutnya, Islam memandang penting kekuasaan politik.
Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pembentukan negara atau pemerintahan itu merupakan salah satu ajaran dasar Islam. Dalam ungkapan lain, kekuasaan politik diperlukan oleh umat Islam, tetapi bukan karena tuntutan agama, melainkan tuntutan situasi sosial dan politik itu sendiri.
Terlepas dari adanya berbagai paradigma hubungan agama dan negara serta berbagai kecenderungan dalam menemukan jawaban Islam bagi konsep tentang negara, unifikasi agama dan negara dalam kenyataan sejarah Islam masih memerlukan pembuktian hakiki.
Pada masa klasik, kala kekuasaan negara berada dalam dominasi penguasa kaum Muslim dan rakyat terdiri dari kaum Muslim, unifikasi agama dan negara hanya berada pada tingkat formal, tetapi proses politik kenegaraan tidak sepenuhnya memantulkan etika dan moralitas Islam.
Begitu pula, beberapa eksperimentasi negara Islam di masa modern, ketika kekuasaan negara juga berada di bawah dominasi penguasa Muslim dan rakyat terdiri dari mayoritas pemeluk Islam, ia masih dihadapkan pada pertanyaan tentang kualitas implementasi nilai-nilai Islam.
Penerapan nilai-nilai Islam, dalam hal ini terkesan formalistik dan juristik dalam bentuk pemberlakukan hokum-hukum positif berdasarkan norma-norma Islam. Beberapa prinsip Islam tentang pemerintahan dan kenegaraan seperti prinsip demokrasi, persamaan hak politik, dan kebebasan politik, belum menjelma dalam kenyataan.