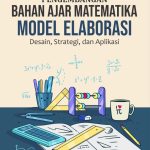Samudrabiru – Tasawuf atau sufisme atau mistisisme merupakan fenomena keagamaan yang selalu ada dalam tradisi agama-agama di dunia. Dan kata sufisme ini istilah Orientalis Barat khusus digunakan untuk mistisisme Islam. Sufisme tidak digunakan untuk mistisime yang terdapat dalam agama-agama lain (selain Islam). tetapi kapan lahirnya tidak bisa dipastikan. Ketidakpastian ini juga terjadi pada penelusuran asal-usul kata sufi yang membentuk istilah tasawuf itu.
Setidaknya ada tiga pendapat besar yang menyebutkan tentang asal-usul kata shūfī. Pertama, berasal dari kata shūf (kain yang dibuat dari bahan wool). Penggunaan baju ini melambangkan asketisme dan penolakan terhadap kenikmatan material (renunciation). Terkait dengan kata shūf (wool) yang menjadi tashawwuf, menurut Imam as-Suhrawardi, pemilihan kata tersebut sebenarnya telah sesuai dari segi asal-usulnya. Tashawwuf artinya berpakaian wool, seperti kata taqammus (berkemeja).
Kedua, kata shūfī diambil dari sebutan Ahl al-Shuffah, orangorang yang ikut pindah dengan nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Mereka ini kaum miskin papa. Namun dari tinjauan bahasa, pendapat ini tidak menunjukkan rangkaian logis. Karena nisbah dari kata al-shuffah bukan shūfī, melainkan shuffī. Ketiga, dari kata sophos (Yunani) yang artinya hikmah. Penyebutan kata sufi dari sophos ini sedikit bisa dipercaya.
Dalam konteks Islam, diperkirakan sufisme lahir sejak turunnya al-Qur’an, namun baru pada awal abad ke-8 M (ke-2 H) mulai dikenal. Di antara tokoh sufi yang hidup pada masa itu adalah: pertama, Sufyan al-Tsauri (w. 135H), Abu Hasyim (w. 150), Jabir Ibn Hisyam (w. 190), Hasan al-Bashri (w. 110H), Rabi’ah al-Adawiyyah (w. 185) dari kelompok Kuffah dan Basrah; kedua, Ibrahim Ibn Adham (w. 162H), Syafiq al-Balkhi (w. 194H), dari Persia; dan ketiga, Ja’far al-Shadiq (w. 148), dari Madinah. Pada mulanya mereka ini bersikap zuhd (asketis) dengan berpakaian dari wool yang kasar, kemudian meningkat menjadi ajaran tasawwuf.
Tentang definisi istilah tasawuf kalangan muslim tidak mempunyai satu kesepakatan pengertian. Hal ini terjadi karena tasawuf telah menjadi semacam milik bersama berbagai agama, filsafat, dan kebudayaan dalam berbagai kurun dan masa. Lebih lanjut al-Taftazani menyatakan bahwa dalam kenyataannya setiap sufi ataupun mistikus selalu berusaha mengungkapkan pengalamannya dalam kerangka ideologi dan pemikiran yang berkembang di tengah masyarakatnya, ini berarti ungkapanungkapannya itu tidak dapat bebas dari kemunduran dan kemajuan kebudayaan zamannya sendiri. Menurut Abu Yazid al-Busthami, “tasawuf mencakup tiga aspek, yaitu khā’ (takhallī), mengosongkan diri dari perangai yang tercela, hā› (tahallī) menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan jīm (tajallī) mengalami kenyataan ketuhanan. Ma’ruf al-Karkhi (w. 200H), Zunnun al-Mishri (w. 246), dan al- Syibli (w. 334) menyebutkan bahwa tasawuf adalah ketidakpedulian terhadap kenyataan dan mengabaikan apa yang ada di tangan makhluk. Al-Hallaj (w. 309H) menekankan bahwa tasawuf sebagai keesaan zat, yang tidak dapat menerima seseorang dan seseorang tidak pula menerimanya. Ibn al-’Arabi (w. 638H) menyatakan bahwa tasawuf sebagai berakhlak sesuai dengan akhlak Allah swt. Namun beberapa pengertian yang berkembang dan sering digunakan sebagai acuan adalah pengertian tasawuf menurut al-Junaid al-Baghdadi (w. 297H/910M). Menurut “bapak tasawuf moderat” ini tasawuf didefinisikan sebagai keberadaan bersama Allah swt tanpa adanya penghubung.
Definisi tasawuf yang dikemukakan oleh al-Junaid sebagaimana dikutip Shimel—tersebut didasarkan pada penglihatannya terhadap prototipe para rasul yang disebut dalam al-Qur’an, Nabi Ibrahim as, Nabi Ismail as, Nabi Ayub as, Nabi Zakaria as, Nabi Yunus as, Nabi Isa, Nabi Musa as, dan Nabi Muhammad saw. Secara rinci tasawuf didasarkan pada delapan sifat yang dicontohkan oleh delapan rasul, sebagai berikut: Pertama, kedermawanan Ibrahim, yang mengorbankan putranya. Dalam literatur Islam, Nabi Ibrahim dikenal sebagai Teman Allah (Khalil Allah, Friend of God). Dalam konteks lintas agama (terutama agama-agama Semitik, Yahudi, Kriten, dan Islam), sebutan ini diiringi sejumlah kesaksian tertulis bahwa untuk bias mencapai gelar tersebut Nabi Ibrahim harus melintasi sejumlah rintangan dan tantangan, baik dari lingkungan masyarakatnya (Raja Namrut yang penyembah berhala), lingkungan dari keluarganya (Azar, Sang ayah yang pembuat berhala), maupun ujian dari bagian dirinya sendiri, yaitu harus menyembelih putra tercintanya (seorang anak yang shalih yang telah dirindukannya puluhan tahun lamanya).
Nabi Ibrahim dikenal sebagai Bapak para Nabi (Abu al-Anbiya, Father of the Prophets). Disebutnya sebagai Bapak para Nabi, karena dari Nabi Ibrahim lahir para nabi-nabi yang mempunyai pengikut luar biasa. Dalam perkembangannya para pengikut ajaran keturunan Nabi Ibrahim inilah yang mewarnai kehidupan saat ini. Ia menikah dengan dua orang perempuan sekaligus, Siti Hajar dan Siti Sarah. Tanpa istri-istri Ibrahim tersebut peradaban agama-agama semitic (Semitic Civilization) tidaklah ada. Sebagaimana yang ditulis oleh Kushel, “Without the primal mothers these would be no Jewish, Hristian or Islamic civilization.” Dalam suasana konflik yang berkepanjangan, kehadiran Yahudi, Kristen, dan Islam menjadi fenomena yang kompleks, bahkan mewarnai sebagian besar di setiap benua yang tersebar di bumi.
Urgensi kehadiran Ibrahim dalam agama samawi bukan saja diikuti apa yang selama ini menjadi ajarannya, namun dalam kegiatan ritual-ceremonial keagamaan, nama Ibrahim senantiasa disebut. Secara sosio-historis penyebutan nama Ibrahim tersebut sebagai bentuk penegasan komitmen masing-masing orang untuk menyatakan diri sebagai bagian besar dari tradisi/millah Ibrahim. Seperti dalam shalat (ritual, liturgy) orang Muslim, Kristen dan Yahudi.
Namun hal terpenting lainnya dari Nabi Ibrahim adalah sebutannya sebagai seorang yang hanif. Bahkan al-Qur’an menegaskan bahwa nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi bukan pula seorang Nasrani, melainkan seorang yang hanif.
Secara harfiah hanif berasal dari hanafa—hanfan: maala; tahannafa—shaara hanifiyan aw ‘amila ‘amala al-hanifiyyah. Alhanif (sg), al-hunafaa’ (plr): al-mutamassiku bi al-Islam (berpengang teguh pada Islam) aw al-shahih al-mayl ilaihi. Kullu man kaana ’alaa Diin Ibraahiim (setiap orang yang mengikuti agama Ibrahim). Almuwahhid fi Diinihi (bertauhid dalam agamanya). Al-Mustaqim (lurus).
Dalam penjelasan Mu’jam al-’Arabiyah al-Mu’ashirah disebutkan bahwa hanif : 1) merupakan sifat mirip yang menunjukkan pada ketetapan orang yang condong (cenderung); 2) Nasik (orang yang beribadah); kecenderungan baik pada Islam yang tetap, lurus berupaya pada agama yang benar. Hanifii, kata yang disandarkan pada hanif, menyandarkan pada agama yang diseur oleh Ibrahim as. Hanifiiyah isim mu’anats yang disandarkan pada hanif ”millata hanifiyah” ahabbu al-adyaan ilaa Allaah al-hanifiiyah al-samhah. Al-hanifiiyah al-syar’ al-mab’uts bihi al-rusul ’ala altauhid. Dalam istilah teknis bahasa Inggris hanif diartikan (one by nature upright). Hanif adalah kecenderungan dasar manusiawi yang selalu mengajak dan mendorong manusia agar mencintai dan merindukan yang benar.
Kedua, kepasrahan Ismail, yang menyerahkan diri pada perintah Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Kisah kehidupan nabi Ismail sangat dengan ritual ceremonila haji umat Islam. Mulai dari ibadah sa’i hingga pengorbanan seekor domba. Al-Qur’an menyebut Ismail memiliki karakter sebagai anak yang sangat sabar (ghulamun halimun). Puncak kesabaran seorang anak bernama Ismail ini ia tunjukkan ketika nabi Ibarahim mendapat wahyu dari Allah melalui mimpinya untuk mengorbankan Ismail.
Dalam penjelasan ayat-ayat yang lain Nabi Ismail disebutsebut sebagai orang yang sabar, mendapat wahyu dari Allah sebagaimana para nabi-nabi yang lain, yang punya komitmen pada janjinya yang benar, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkannya, termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, bersama nabi Ibrahim as (ayahnya) membangun dan memelihara Ka’bah, sebagai lokus fisik umat Islam menghadapkan arah ibadahnya.
Ketiga, kesabaran Ayub, yang dengan sabar menahan penderitaan penyakit gatal dan kecemburuan Yang Maha Pemurah. Tidak banyak ayat al-Qur’an yang mengkisahkan nabi Ayub ini. Q.S. al-Anbiya/21: 83, ”dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”
Keempat, perlambangan Zakaria, yang menerima sabda Tuhan, “Kau tak akan berbicara dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan mempergunakan lambang-lambang” (Q.S. Ali ‘Imrān [3]: 36) dan juga “tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut” (Q.S. Maryam [19]: 2). Dalam al-Qur’an Nabi Zakariya merupakan tokoh penting dalam proses pendidikan Maryam ibunda Isa al-Masih. Bertahun-tahun dia berdoa pada Tuhan agar dikarunia seorang putra yang melanjutkan risalah kenabian dengan sentuhan bahasa yang menggambarkan kemustahilan punya keturunan. Istrinya sudah tua dan rambutnya sudah beruban. Suatu ungkapan yang bermakna keputusaan. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Isyarat-isyarat yang tidak umum supaya dilakukannya, dengan cara berpuasa tidak bicara, kecuali dengan isyarat-isyarat.
Kelima, keasingan Yunus, yang merupakan orang asing di negerinya sendiri dan terasing di tengah-tengah kaumnya sendiri. Nabi Yunus mengalami keterasingan sosial, keberadaan yang hilang di tengah masyarakatnya. Selain mengalami keterasingan dari kaumnya, Nabi Yunus pernah dilempar dari sebuah perahu yang keberatan beban. Dalam keadaan terlembar di laut itulah, Nabi Yunus disambut dengan ikan besar dan menelannya beberapa hari.
Dalam keterasingan di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak putus-putus dalam doa. Dan Allah telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari pada kedukaan.
Keenam, sifat penziarah nabi Isa, yang begitu melepaskan keduniawian sehingga hanya menyimpan sebuah mangkuk dan sebuah sisir – mangkuk itu dibuangnya ketika ia melihat seseorang minum dari telapak tangannya, dan juga sisirnya ketika dilihatnya seseorang menyisir rambut dengan jari-jarinya. Bukan hanya itu al-Qur’an merekam kehidupan nabi Isa sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga begitu dekatnya nabi Isa diberi izin untuk melakukan tindakan di luar batas kemampuan manusia umum. Di antara yang dilakukan atas izin Allah adalah: berbicara ketika masih dalam buaian, meniup patung burung sehingga bisa hidup, menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit sopak, dan mengeluarkan orang mati dari dalam kubur dan menjadi hidup.
Ketujuh, pemakaian jubah wool oleh Musa. Kesederhanaan nabi Musa memang patut dijadikan teladan. Kelahirannya sudah mulai hidup dalam keterasingan ketika pada masa Fir’aun menerima mimpi bahwa akan ada anak lelaki yang kelak mengalahkan dirinya. Hingga bayi-bayi lelaki yang lahir di masa itu dibunuh. Namun Tuhan punya cerita lain, bahwa bayi Musa dimasukkan ke dalam keranjang lalu dihanyutkan oleh ibunya ke sungai Nil. Namun hal yang mungkin tidak masuk dalam pemikiran nabi Musa adalah ajaran yang diterima olehnya dari nabi Khidzir. Dalam pertemuan kedua orang shalih di tepian pantai itu, nabi Musa ditunjukkan peristiwa yang tidak masuk akal. Seperti, nabi Khidir merusak kapal, membunuh anak kecil, mendirikan tembok rumah yang roboh. Apa yang dilakukan oleh nabi Khidir di luar kemampuan nalar nabi Musa. Namun pertemuannya dengan nabi Khidir itu membuka fakta lain bahwa terdapat peristiwa yang tidak harus menuntut adanya sebab musabab empiris rasional.
Kedelapan, kemelaratan Muhammad, yang dianugerahi kunci segala harta yang ada di muka bumi oleh Tuhan, sabdaNya, “Jangan menyusahkan diri sendiri, tapi nikmati setiap kemewahan dengan harga diri,” namun jawabnya, “Ya Allah, hamba tidak menghendakinya; biarkan hamba sehari kenyang dan sehari lapar.” Nabi Muhammad pada al-Qur’an yang Allah turunkan langsung melalui Malaikat Jibril. Kitab Suci yang menjadi mu’jizat kerasulan nabi Muhammad.
Berdasarkan definisi di atas Ibrahim Basyuni—sarjana muslim berkebangsaan Mesir—mengkategorikan pengertian tasawuf pada tiga hal, berikut ini. Pertama, kategori al-bidāyah. Suatu sikap yang menekankan kecenderungan jiwa dan kerinduannya secara fitrah kepada Yang Maha Mutlak, sehingga orang senantiasa berusaha mendekatkan kepada Allah swt. Kedua, kategori al-mujāhadāt. Suatu pengertian yang membatasi tasawuf pada pengamalan—yang lebih menonjolkan akhlak dan amal dalam mendekatkan diri kepada Allah swt—yang didasarkan atas kesungguhan. Ketiga, al-mazāqāt. Suatu pengertian yang cenderung membatasi tasawuf pada pengalaman batin dan perasaan beragama, terutama dalam mendekati Zat Yang Mutlak.
Judul : Mengenal Dunia Sufisme Islam
Penulis : Aris Fauzan
Penerbit : Samudra Biru, Cetakan I, Desember 2018
Dimensi : viii + 148 hlm. ; 15 x 23 cm.
Harga : Rp