MONOFTONG DALAM BAHASA ACEH Variasi Dialek Berdasarkan Fonetik Akustik
Buku ini mencakup berbagai topik mulai dari teori-teori dasar
perdagangan internasional, kebijakan tarif dan non-tarif, neraca
perdagangan, hingga isu-isu kontemporer seperti perjanjian dagang
regional, perang dagang, serta peran teknologi dan digitalisasi dalam
mempercepat arus perdagangan global
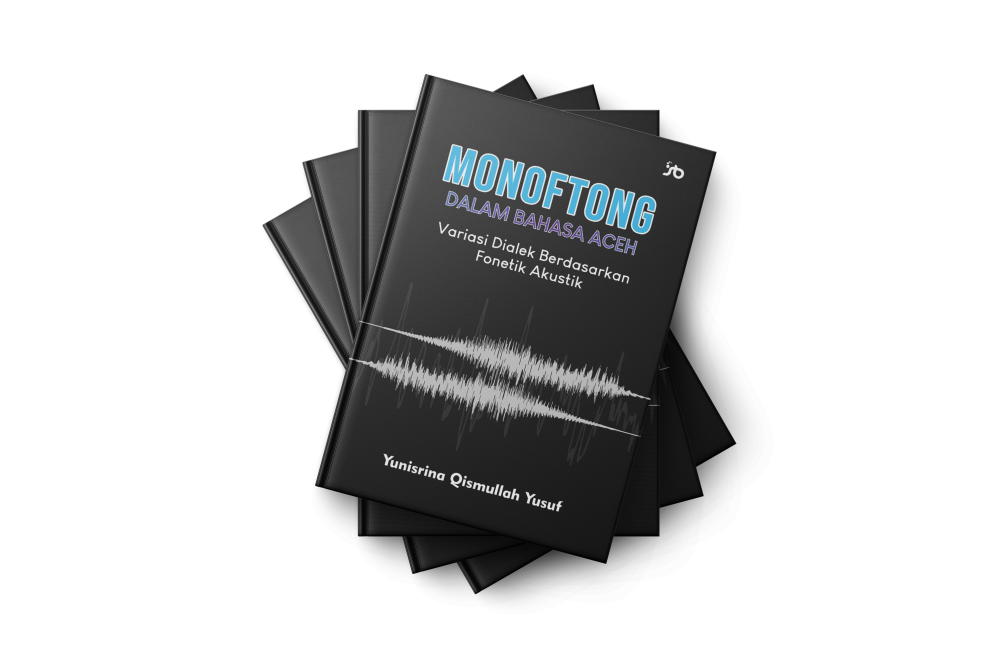
Pergeseran Bahasa Aceh
Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatra, Indonesia. Provinsi ini memiliki status otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Wilayah Aceh terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota, dengan Banda Aceh sebagai ibu kota yang terletak di pesisir utara pulau tersebut. Selain kondisi geografis dan administratif, kehidupan masyarakat Aceh juga dapat dilihat dari penggunaan bahasanya. Bahasa resmi yang digunakan di Aceh adalah bahasa Indonesia, sebagaimana berlaku di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam konteks formal seperti pendidikan, pemerintahan, dan pertemuan resmi. Meski demikian, berbagai bahasa daerah tetap hidup dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi informal.
Penggunaan bahasa daerah yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi alasan pentingnya pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Walaupun pengajaran bahasa daerah di sekolah negeri tidak diwajibkan, tetapi pelestarian bahasa daerah tetap menjadi perhatian penting di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 32 Ayat 2 (dalam Redaksi Jogja Bangkit, 2010) menegaskan bahwa bahasa-bahasa daerah milik bangsa Indonesia harus dihormati dan dilestarikan oleh pemerintah sebagai bagian dari warisan budaya nasional (Lumintaintang, 2002; Sulaiman, 1978). Oleh karena itu, banyak sekolah negeri di Indonesia yang mengajarkan bahasa daerah dan memasukkannya ke dalam kurikulum sebagai upaya pelestarian.
Di Aceh, bahasa Aceh diajarkan di sekolah negeri pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dari kelas VIII hingga kelas IX, dengan durasi sekitar dua jam per minggu (Akmal, 2011). Materi yang diajarkan mencakup struktur kalimat, keterampilan menulis, dan kosakata. Hal serupa juga diterapkan di sekolah-sekolah keagamaan, seperti pesantren atau dayah, yang bahkan mengajarkan bahasa Aceh dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan durasi waktu belajar yang sama.
Meskipun bahasa Aceh masih digunakan dalam lingkungan keluarga dan sosial, terutama di desa-desa, keberadaannya kini menghadapi tantangan yang semakin besar dari dominasi bahasa Indonesia (Akmal, 2011; Alamsyah, Taib, Azwardi & Idham, 2011). Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda Aceh secara bertahap lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh (lihat Alamsyah, Taib, Azwardi & Idham, 2011).
Keberagaman etnis di Aceh turut memengaruhi dinamika bahasa di provinsi ini. Aceh dihuni oleh berbagai kelompok etnis. Kelompok etnis utama di provinsi ini adalah suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jame, dan Kluet (Wu, 2006), dengan sekitar 90% penduduknya berasal dari etnis Aceh (McCulloch, 2005). Selain itu, terdapat juga kelompok etnis yang lebih kecil seperti Ulu Singkil dan Simeulu (McCulloch, 2005). Beberapa etnis minoritas lain di provinsi ini antara lain adalah Minangkabau, Jawa, dan
Tionghoa (Taylor, 2011).
Bahasa Aceh merupakan salah satu bahasa daerah yang masih hidup dan digunakan secara aktif oleh masyarakat di Aceh, Indonesia, serta oleh komunitas keturunan Aceh yang telah menetap sejak abad ke-18 di Kampung Aceh, Kedah, Malaysia. Keberadaan komunitas ini menunjukkan dinamika bahasa yang menarik untuk dikaji, terutama bagaimana bahasa Aceh bertahan dan berkembang di luar wilayah asalnya. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai sistem vokal dalam bahasa Aceh, dengan fokus khusus pada dua kelompok penutur utama, yakni masyarakat Aceh di wilayah asal mereka (Ach) dan keturunan Aceh di Malaysia (KpA).
Kajian dalam buku ini berfokus pada analisis produksi bunyi vokal, khususnya monoftong, yang diperoleh dari dua konteks ujaran: ujaran elisitasi menggunakan daftar kata dan tuturan alami dari sesi wawancara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana vokal dipertahankan, berubah, atau hilang dalam kontak dengan Bahasa Melayu Standar dan dialek Kedah, sekaligus mencerminkan interaksi bahasa dan budaya penutur Aceh dengan lingkungan sekitar.
Selain aspek linguistik, buku ini juga mengulas bagaimana variasi vokal yang dihasilkan oleh penutur KpA mencerminkan identitas sosial mereka. Identitas ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan hasil dari proses pembentukan identitas Aceh Malaysia yang unik dan dinamis. Memahami variasi fonetik menunjukkan bagaimana bahasa mencerminkan sejarah, migrasi, dan hubungan sosial komunitas.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI
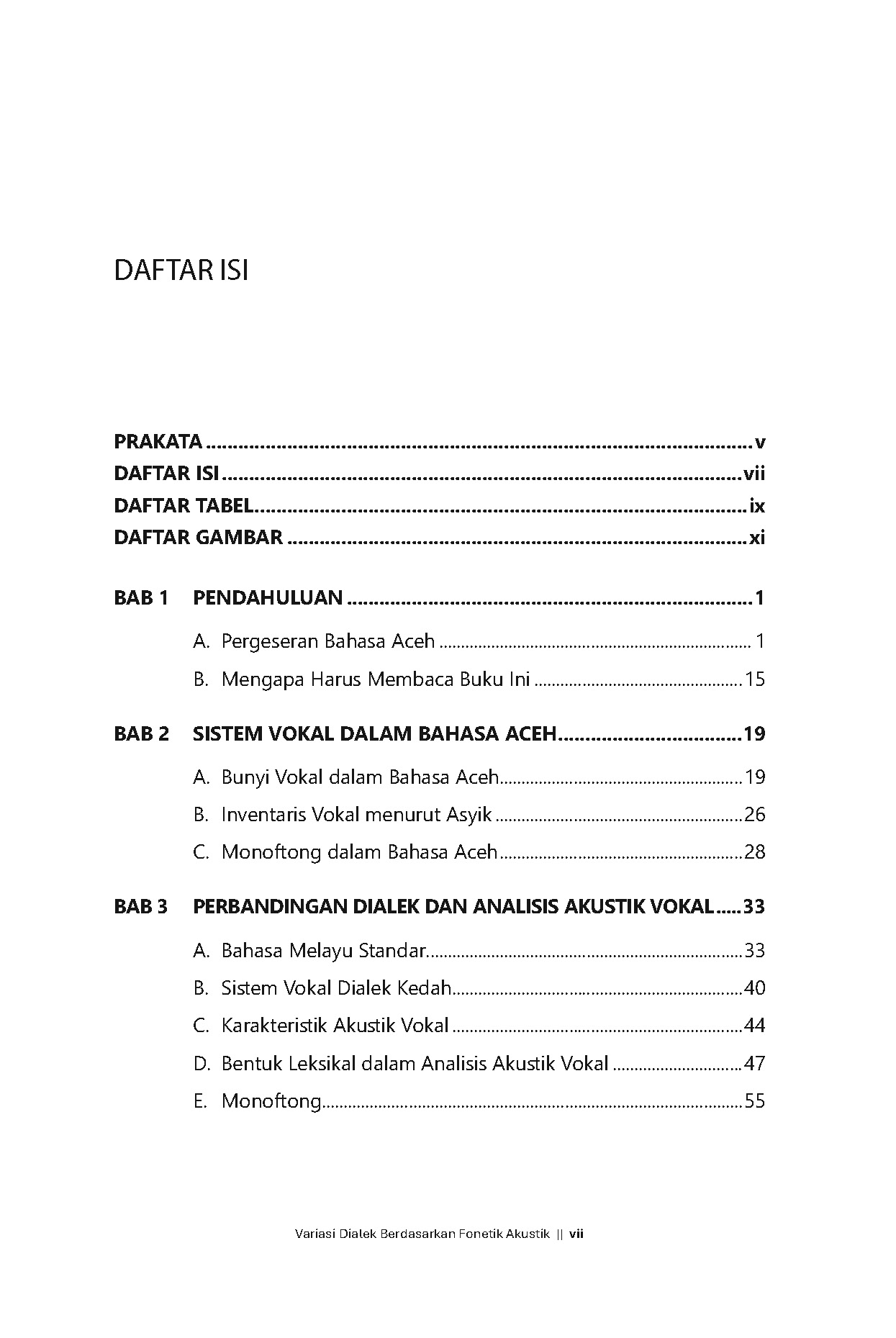 Daftar Isi 1
Daftar Isi 1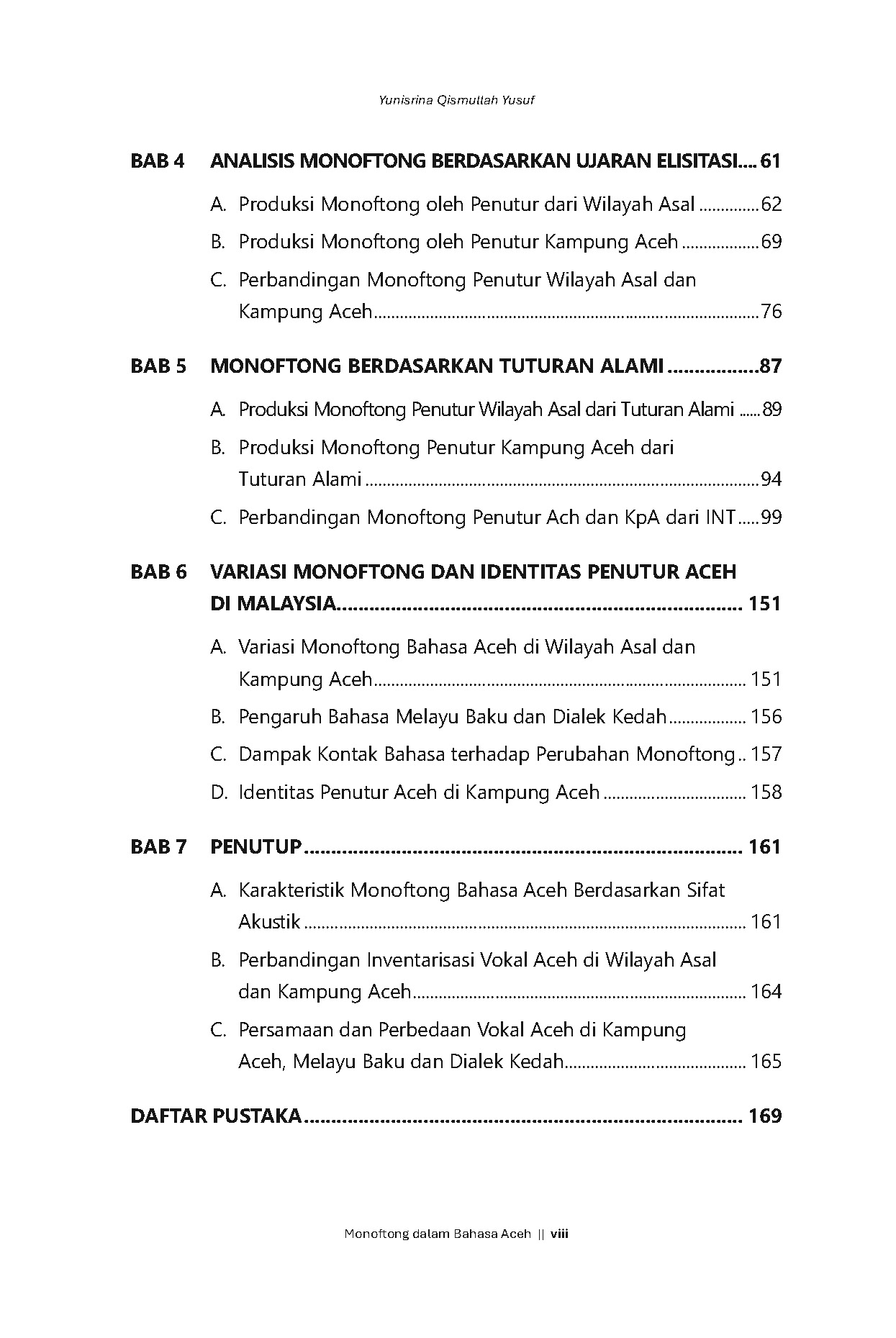 Daftar Isi 2
Daftar Isi 2Spesifikasi Buku
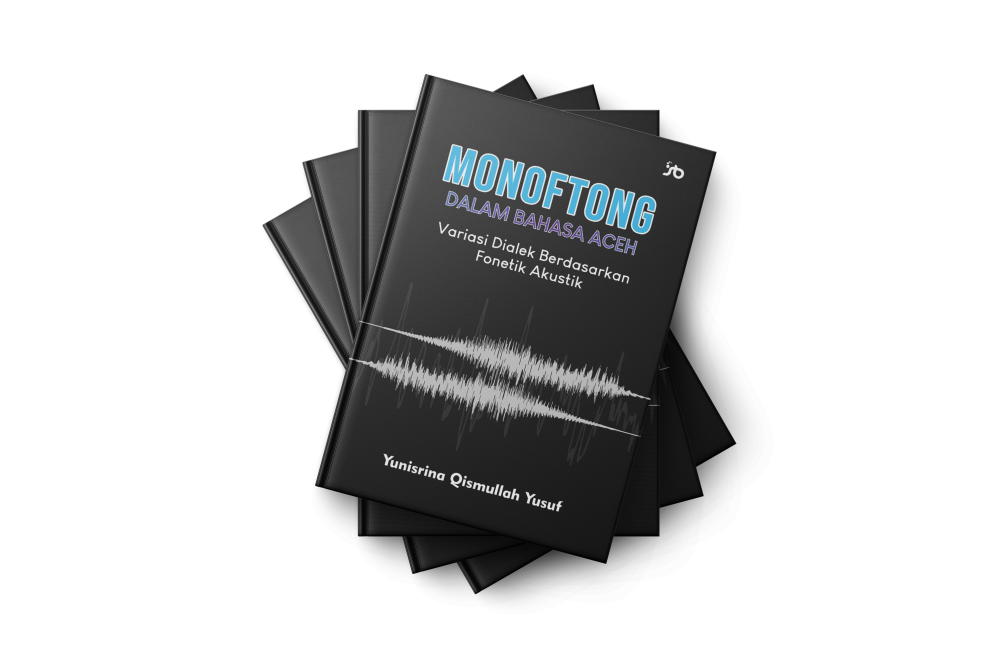
Cetakan I, Juni 2025; 202 hlm, ukuran 15,5 x 23 cm, kertas isi Bookpaper hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 125.000
Rp 121,600
Tentang Penulis

Prof. Yunisrina Qismullah Yusuf
Pendidikan: S1 PBI Unsyiah (lulus 2002), S2 Linguistics (2006) – S3 Phonology (2013), University Malaya.