TRANSFORMASI DAN REKONSILIASI KONFLIK DI INDONESIA
Buku ini menelaah penggunaan bentuk-bentuk lokal transformasi
konflik, dialog, dan rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian atau
perubahan konflik dan pembangunan perdamaian di ketiga wilayah
tersebut.
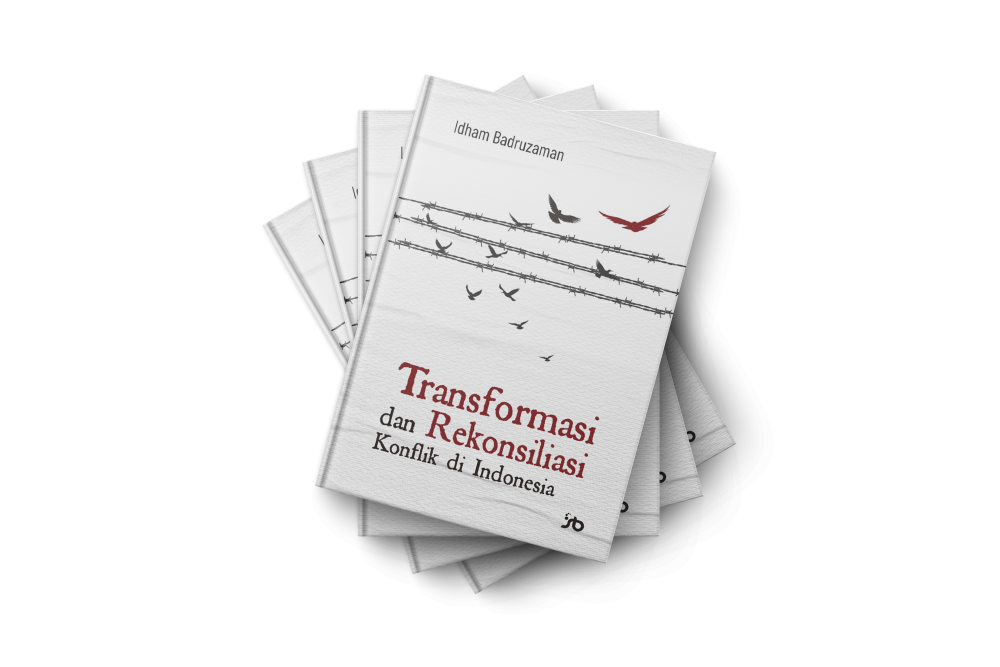
Komunal di Indonesia
Setelah runtuhnya rezim otoriter Presiden Suharto (12 Maret 1967–21 Mei 1998) pada tahun 1998, Indonesia memperkenalkan sistem pemerintahan baru dengan desentralisasi sebagai salah satu ciri utamanya. Desentralisasi menyebabkan pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah bertanggung jawab atas semua urusan kecuali kebijakan luar negeri, keamanan dan pertahanan, peradilan, serta urusan moneter dan fiskal. Kewenangan lainnya mencakup kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga ekonomi negara, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi strategis tinggi, konservasi, serta standardisasi nasional (Republik Indonesia, 1999).
Namun, selama masa transisi ini, Indonesia mengalami konflikkonflik parah dan sulit diselesaikan yang menyebabkan ribuan korban jiwa, sebagian besar warga sipil. Meskipun kerusuhan muncul di banyak wilayah, terdapat tiga daerah yang paling rentan terhadap eskalasi menjadi kekerasan berdarah akibat ketegangan politik, etnis, dan agama: (1) Provinsi Aceh, di mana isu separatisme menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa (Collier, Sambanis, & World Bank, 2005); (2) Sampit di Kalimantan Tengah, di mana lebih dari 500 orang dari etnis Dayak dan Madura tewas dalam bentrokan yang dikategorikan sebagai konflik etnis (Fanselow, 2015); dan (3) Ambon di Kepulauan Maluku, di mana konflik agama menyebabkan lebih dari 1.000 korban dari umat Islam dan Kristen (Wilson, 2005; Schulze, 2017). Setiap kasus ini akan dibahas secara terpisah dalam bab tersendiri.
Buku ini menelaah penggunaan bentuk-bentuk lokal transformasi konflik, dialog, dan rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian atau perubahan konflik dan pembangunan perdamaian di ketiga wilayah
tersebut. Fokus utamanya adalah pada peran masyarakat lokal dalam proses pembangunan perdamaian. Penelitian ini mencakup analisis terhadap dimensi historis, budaya, agama, dan politik
dari praktik-praktik transformasi konflik konvensional, dialog, dan rekonsiliasi. Sebagian besar kajian akademik tentang transformasi konflik cenderung mengabaikan atau meremehkan peran praktik
lokal atau adat, dan lebih menekankan strategi penyelesaian konflik yang dipaksakan dari luar.
Dalam konteks Indonesia, dua penelitian terbaru oleh Birgit Bräuchler dan Qurtubi menunjukkan keberhasilan transformasi konflik dan rekonsiliasi berbasis lokal di Ambon. Salah satu contohnya adalah musyawarah, pendekatan dialog yang telah lama digunakan dalam komunitas minoritas rukun tetangga (sekitar 80 keluarga). Musyawarah dilakukan secara rutin sebulan sekali atau lebih sering bila dibutuhkan, dan terbukti efektif dalam meredam kekerasan komunitas (Ahnaf, 2016). Contoh lainnya adalah pela dan gandong—perjanjian budaya antar desa yang tetap dijalankan tanpa memandang perbedaan agama. Keduanya sangat bermanfaat dalam proses rekonsiliasi dan transformasi konflik (Bräuchler, 2015).
Di Sampit, Mapas Lewu menyatukan masyarakat Madura dan Dayak dalam kegiatan tahunan yang turut memperkuat rekonsiliasi dan menjaga perdamaian. Sementara itu, di Aceh, tradisi pemulia
jamek atau ‘menyambut tamu’ dimanfaatkan oleh Farid, seorang negosiator informal pemerintah, untuk membantu proses perdamaian dan mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari
28 tahun. Bentuk-bentuk kearifan lokal semacam ini akan dibahas secara rinci dalam bab studi kasus.
Akhirnya, berbagai monumen didirikan untuk mengenang peristiwa masa lalu dan mencegah pengulangan tragedi serupa. Gong perdamaian besar dibangun di pusat kota Ambon; monumen
perdamaian berdiri di bundaran jalan utama kota Sampit; dan balai perdamaian telah didirikan di ibu kota Provinsi Aceh. Peringatan akan tragedi kemanusiaan serupa juga terdapat di berbagai tempat
lain seperti Gernika Peace Museum Foundation di Spanyol, Hiroshima Peace Memorial Museum di Jepang, dan Memorial Hall of the Victims di Nanjing, Tiongkok.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI
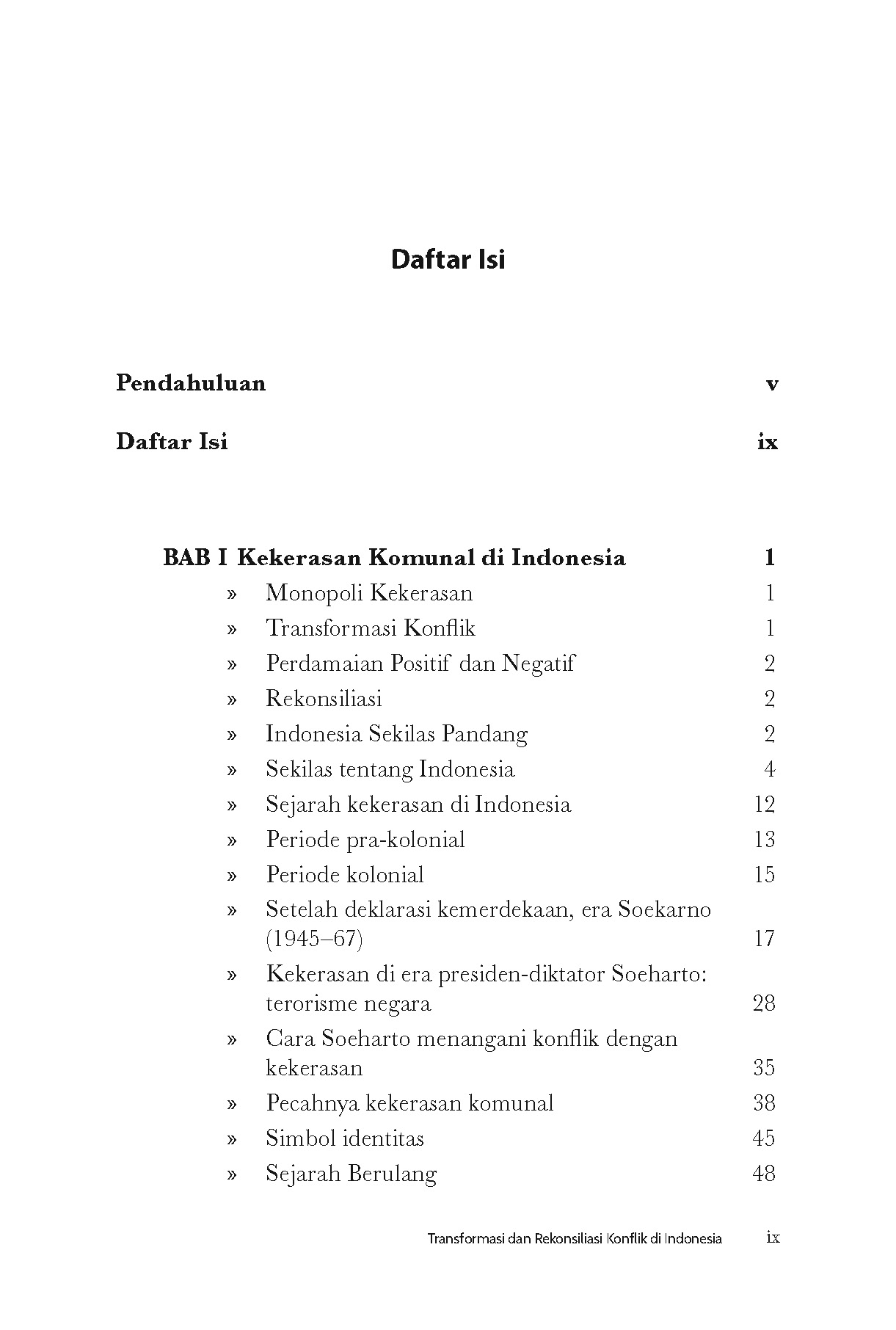 Daftar Isi 1
Daftar Isi 1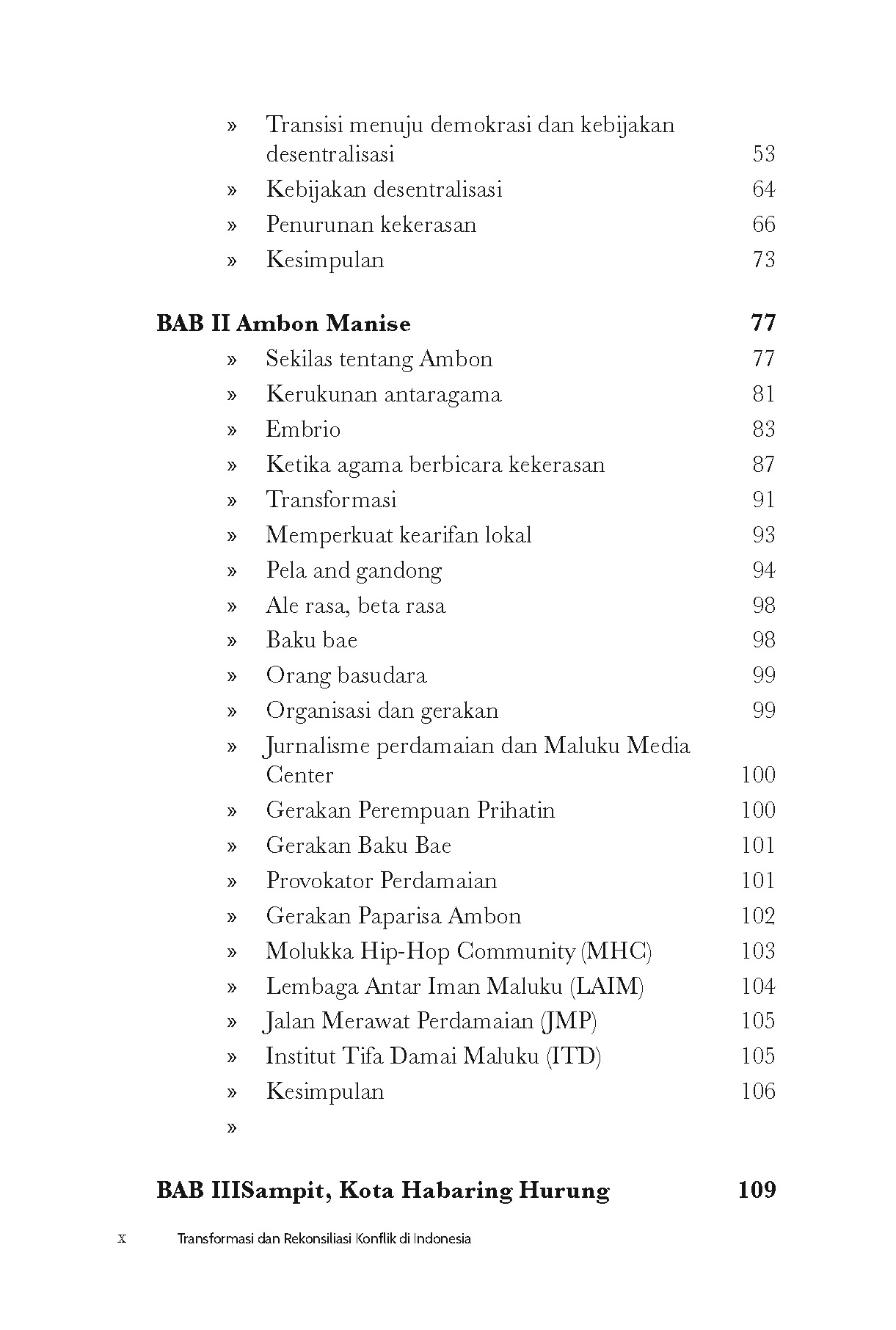 Daftar Isi 2
Daftar Isi 2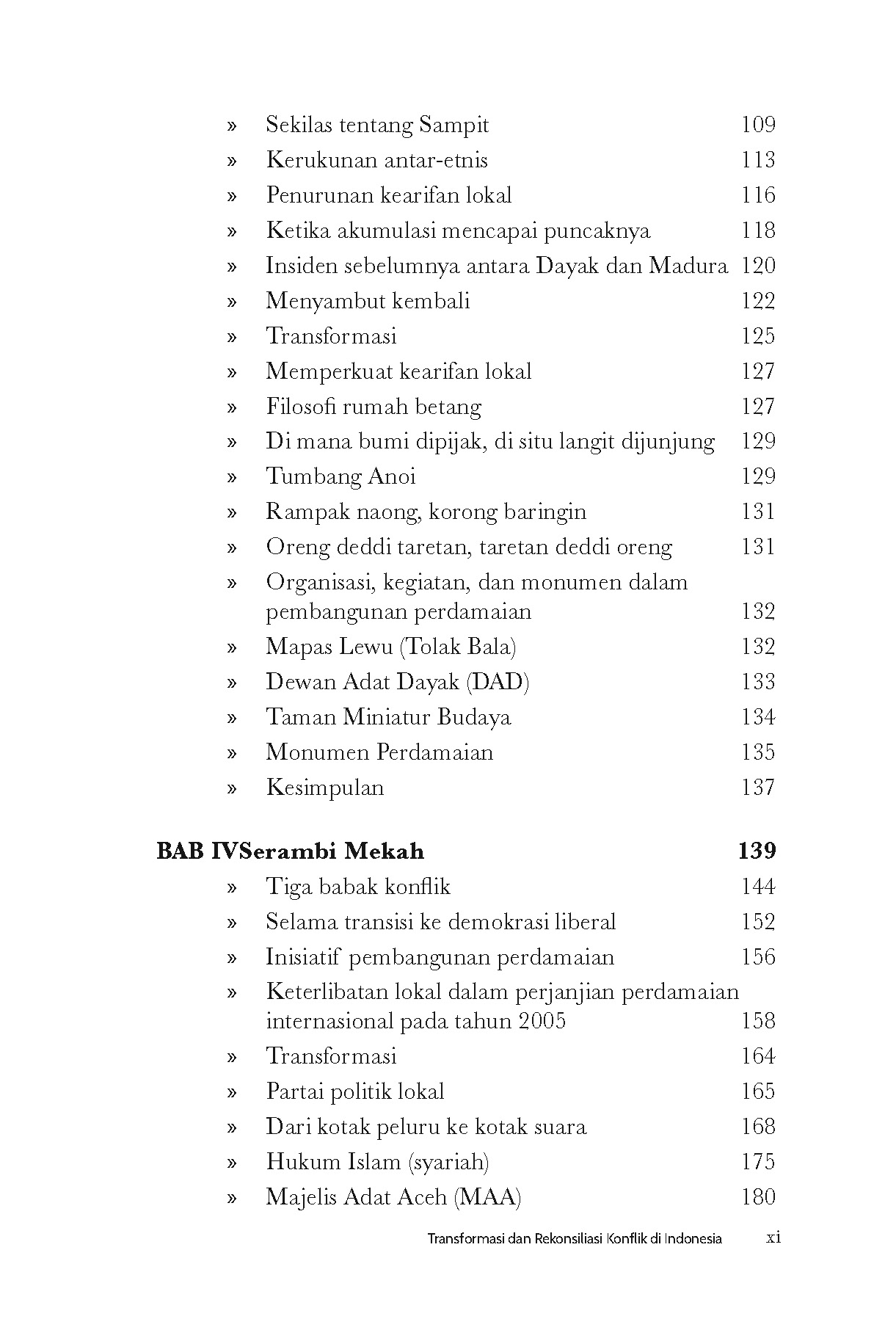 Daftar Isi 3
Daftar Isi 3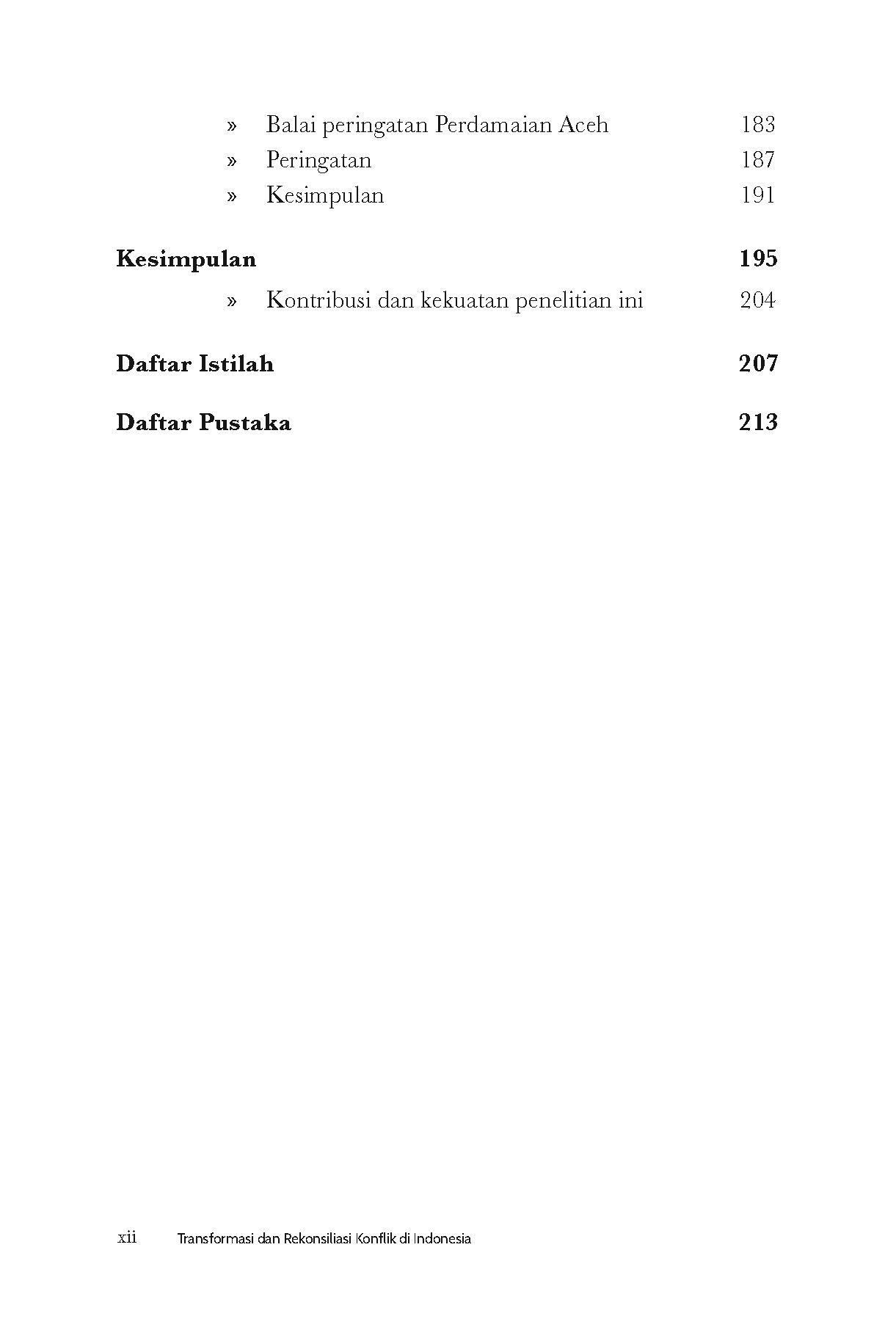 Daftar Isi 4
Daftar Isi 4Spesifikasi Buku
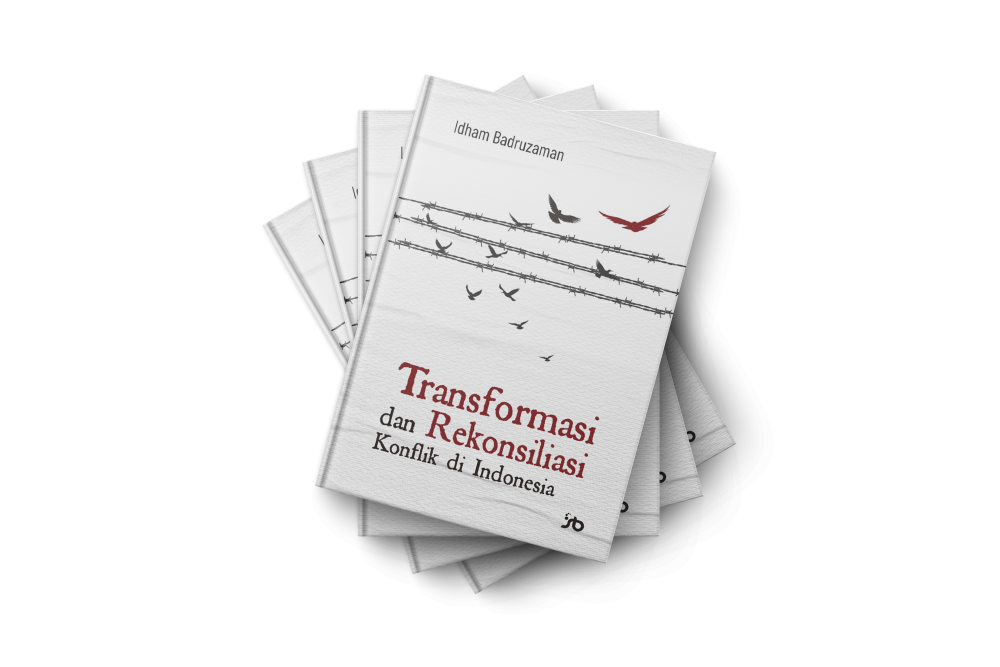
Cetakan I, Juni 2025; 253 hlm, ukuran 15,5×23 cm, kertas isi Bookpaper hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 150.000
Rp 140,500

Tentang Penulis

Idham Badruzaman
menghabiskan enam tahun di Spanyol untuk menyelesaikan studi master di Universitat Jaume I dan program doktornya di Universidad Autónoma de Madrid. Selama berada di Spanyol, Ia ikut menyempatkan diri untuk mempelajari bahasa dan menggali sejarah negara tersebut, menumbuhkan apresiasi yang mendalam terhadap aspek sosial dan budaya Kerajaan Spanyol. Kecintaannya yang mendalam pada Spanyol tercermin dalam Buku pertamanya tentang Spanyol ini dengan judul: Memori Pilu Gernika. Ia telah menganggap negara Spanyol sebagai rumah keduanya, sehingga Ia selalu punya cara untuk dapat mengunjungi negara ini setiap tahunnya sejak Ia menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 2021.
Ketertarikan Idham pada studi perdamaian dimulai ketika mengambil program master di Castellon de Plana – Valencia dengan nama program: Studi Perdamaian, Konflik, dan Pembangunan. Program ini memicu minatnya untuk terus menekuni bidang studi perdamaian dan konflik sehingga menjadi tema sentral dalam penelitian dan tulisannya.
Setelah mendapatkan gelar doktor, Idham kembali ke almamaternya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana Ia kini menjadi dosen di Jurusan Hubungan Internasional sekaligus menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kegemarannya terhadap dunia internasional dimulai ketika Ia menjadi siswa pertukaran pelajar di Seattle – Amerika Serikat melalui Program AFS (America Field Service) pada tahun 2004-2005. Sejak saat itu, Ia menjadi ketagihan untuk menjelajahi belahan dunia yang lain, lagi dan lagi.